(Rujukan bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program kepariwisataan Provinsi Jambi)
Oleh:
Thamrin B. Bachri**
Pariwisata berkelanjutan merupakan topik populer pada era sekarang ini (Branwell & Lane, 2005; Lu & Nepal, 2009; Ruhanen et al, 2015). Terlebih lagi dengan fokus perhatian komunitas global terhadap upaya-upaya mengantisipasi pemanasan global, perubahan iklim, dan perilaku overtourism maka tren pariwisata berkelanjutan juga turut mengemuka (swarbrooke, 2011).
Penetapan resolusi Majelis Umum PBB 70/193 yang menetapkan International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017, ditambah dengan kondisi pandemi global yang sudah berjalan selama hampir dua tahun ini
(2019-2021), mendorong banyak pihak untuk mulai memikirkan nilai-nilai dan bentuk pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan ramah budaya.
Dalam konteks nasional, pariwisata berkelanjutan di Indonesia berkembang selaras dengan dinamika
global. Setidaknya semenjak awal 1990-an wacana pariwisata berkelanjutan sudah mulai disosialisasikan dalam ruang lingkup akademik. Kajian tentang pariwisata berkelanjutan di ruang wilayah Indonesia juga sudah mulai dilakukan pada periode yang sama (lihat wall, 1992,1993), yang mana diikuti juga oleh akademisi Indonesia tidak lama setelahnya (lihat Gunawan, 1997; Salim, 1995).
Patut pula untuk diingat, bahwa pada akhir tahun 1992, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan UNDP, UNESCO, PATA (Pasific Asia Travel Association) dan WTO (World Tourism Organization), menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema Universal Tourism: Enriching or Degrading Culture? (Jafari & Nuryamti, 1993) yang dihadiri 300-an peserta dari 20 negara, yang juga mengangkat sub tema pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu pokok bahasan. Sehingga bisa diasumsikan, pada periode ini konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia mulai diperkenalkan.
Adapun dalam konteks landasan hukum, gagasan pariwisata berkelanjutan tertuang dalam UU RI No
10 Th 2009 tentang Kepariwisataan pasal 2, yang mengatur tentang azas penyelenggaraan kepariwisataan, adapun beberapa landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan berkelanjutan juga tertuang dalam UU RI No 32 Th 2009 tentang PPLH pasal 1 dan 3; UU RI No 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 262 Ayat (1); PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 Pasal 2, 35, 37, 38, 55; dan secara tersirat terindikasi pada PERPRES No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; serta secara eksplisit terutama tertuang pada Peraturan MenPar RI No 14 Th 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Namun demikian, gaung pariwisata berkelanjutan pada tataran pemerintah setidaknya mulai terlihat semenjak digelarnya Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia yang diawali pada tahun 2017 lalu (Kemenpar RI, 2017).
Fenomena tersebut di atas menunjukkan atensi besar dari masyarakat global dan pemerintah terhadap pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, terlepas dari perhatian besar tersebut, kajian empiris sebaliknya menunjukkan bahwa sebenarnya kepariwisataan pada skala global justru sedang berjalan secara tidak sustainable jika dibandingkan sebelumnya (Hall, 2011; Sharpley, 2020).
Contoh-contoh seperti pertumbuhan eksponensial dari perjalanan selama 10 tahun belakangan ini dengan konsekuensi logis berupa meningkatnya emisi karbon, menyusul serangkaian reaksi negatif yang tinggi terhadap pertumbuhan pariwisata di Barcelona, Islandia, atau Venesia yang umumnya dianggap sebagai "keberhasilan" pariwisata namun sebaliknya justru terbukti menimbulkan permasalahan-permasalahan overtourism sebagaimana diulas dalam laporan bersama WTTC & McKinsey & Company tahun 2017 lalu, menggambarkan poin-poin utama yang muncul dari tema overtourism berupa keterasingan penduduk lokal, turunnya pengalaman berwisata, infrastruktur yang kelebihan beban, kerusakan alam, serta ancaman terhadap kebudayaan dan heritage.
Dua tahun ini seluruh dunia termasuk juga Indonesia dihadapkan pada kenyataan pandemi COVID19. Menilik dari sejarah, pandemi berperan dalam perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, sifat dari perubahan tersebut selektif, artinya terkadang minimal, dan di lain waktu, transformasi terjadi secara tidak terduga.
COVID-19 dan langkah-langkah penanggulangannya menyebabkan reorientasi pariwisata dalam beberapa kasus, tetapi dalam kasus lain akan berkontribusi pada kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil pihak. Namun demikian, respons terhadap pariwisata berkelanjutan membutuhkan pendekatan global. Terlepas dari bukti yang jelas tentang kebutuhan ini, kemungkinan transformasi menyeluruh dari sistem pariwisata tetap saja sangat terbatas tanpa transformasi mendasar (Hall et al., 2020).
Singkatnya, pariwisata berkelanjutan menghadirkan paradox (Hall, 2011; Williams & Ponsford, 2009). Pada satu sisi, pariwisata berkelanjutan merupakan keberhasilan mengingat konsep difusi antara industri, pemerintah, akademisi dan pelaku kebijakan untuk mencapai keseimbangan sosialekonomi-lingkungan. Namun, di sisi lain sekaligus merupakan kegagalan kebijakan mengingat pertumbuhan dalam dampak lingkungan akibat dari pariwisata terus terjadi secara absolut (Hall, 2011).
Pada tingkat nasional, pemerintah sebagaimana sudah disinggung di atas, sebenarnya sudah menetapkan bahwa keberlanjutan sebagai salah satu azas pembangunan (UU No 10 Th 2009). Dan pada saat ini, ingin menegaskan kembali komitmen pariwisata berkelanjutan tersebut sebagai paradigma pembangunan pariwisata yang selaras dengan tuntutan masyarakat global (Sustainable Development | UNWTO, n.d.).
Namun paradigma pariwisata berkelanjutan mana yang ingin kita jadikan acuan? Apakah pariwisata berkelanjutan supply driven (lihat Dávid, 2011; Tyler & Dangerfield, 1999)? Ataukah market based (lihat Font & McCabe, 2017; Hardeman et al., 2017)?
Apakah menganut filosofis anthropocentrism atau ecocentrism? (lihat Fennell, 2014; Sheppard & Fennell, 2019). Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana menyeragamkan filosofis ini kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata? Karena pada akhirnya, perbedaan filosofis dalam melihat paradigma pariwisata berkelanjutan ini justru akan menyebabkan tujuan dari berkelanjutan tersebut tidak tercapai.
Tetapi for the sake of berjalannya pelaksanaan program pemerintah, maka kami asumsikan bahwa paradigma pariwisata berkelanjutan yang kita jalankan adalah yang selaras dengan Pancasila dan amanat UUD 1945. Maka dari itu, menjadi bisa dimaklumi jika paradigma pariwisata berkelanjutan kemudian dipasangkan dengan quality tourism (Jennings et al., 2009; Jennings & Nickerson, 2006).
Dimana definisi quality tourism dengan versi yang berbeda diadopsi juga oleh negara-negara seperti India, Kanada, Armenia, dan Selandia Baru, yang meskipun digunakan secara luas, quality tourism tetap menjadi istilah, yang tidak memiliki definisi yang pasti (Jennings et al., 2009).
Namun, perlu digarisbawahi bahwa unsur-unsur “service quality and hospitality sector service experiences; notions of excellence; the perceptions of getting value for one’s money; the matching of expectations with experiences; as well as links between expectations and satisfactions” menggambarkan penggunaan terminologi quality tourism yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Sehingga menjadi jelas bahwa quality tourism ini merupakan konsekuensi dari gagasan service quality (SERVQUAL) yang diusulkan oleh A.Parasuraman et al., (1985, 1988, 1993) dan Zeithmal & Berry (1990) yang condong kepada market orientation tourism.
Sehubungan dengan paradigma pariwisata berkelanjutan dan quality tourism sebagaimana telah diulas di atas, maka kami bisa mengafirmasikan bahwa paradigma pemerintah kita tentang gagasan tersebut memiliki kecenderungan terhadap orientasi pasar. Dimana hal ini memiliki konsekuensi terhadap pengadopsian competitiveness sebagaimana diusung World Economic Forum, yang terdiri dari empat subindeks, 14 pilar dan 90 indikator individu, yang terdistribusikan pada pilar-pilar tersebut.

Akhirnya, paradigma “baru” pariwisata berkelanjutan ini lah yang seharusnya menjadi dasar pemikiran dari pemerintah (Kemenparekraf) dalam mendifusikannya ke dalam 4 (empat) pilar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan pasal 7, dimana pembangunan kepariwisataan meliputi:
a. industri pariwisata;
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.
**Penulis:
• Alumnus Dept. Hospitality & Tourism University of Wisconsin, USA.
• Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Periode
2002-2009.
• Tenaga Ahli Gubernur Jambi.
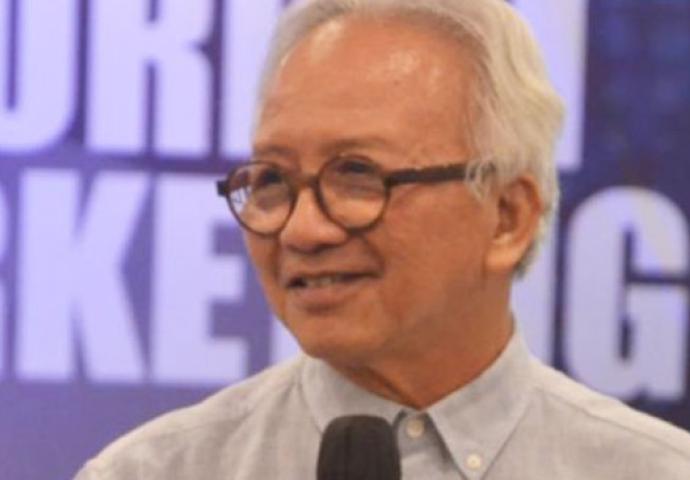

















Comments
Pariwisata berkelanjutan di Indonesia
Tulisan ini merupakan paparan opini berbasis literatur yang baik untuk membingkai arah kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Namun, karena diarahkan sebagai “rujukan” kebijakan Jambi, pembaca akan lebih terbantu jika:
Ada analisis konteks lokal (misalnya data kunjungan wisatawan, daya dukung lingkungan, atau sektor unggulan di Jambi).
Ada peta jalan implementasi yang lebih konkret (misalnya langkah-langkah di empat pilar UU Kepariwisataan: industri, destinasi, pemasaran, kelembagaan).
Ada indikator pengukuran (bagaimana mengukur keberhasilan quality tourism atau sustainability di tingkat provinsi).
Dengan melengkapi aspek-aspek tersebut, tulisan ini berpotensi menjadi dokumen kebijakan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga operasional.
Student
Dengan bergeser ke arah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan sektor pariwisata yang tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang langgeng bagi seluruh rakyatnya.
Pariwisata Berkelanjutan
Terimakasih pak Putra Handara atas masukannya. Artikel ini hanya untuk rujukan konseptual saja bukan rujukan teknis. Memang harus ada pendalaman utk rujukan teknis. Wass tks.
Pariwisata Berkelanjutan
Terimakasih pak Putra Handara atas masukannya. Artikel ini hanya untuk rujukan konseptual saja bukan rujukan teknis. Memang harus ada pendalaman utk rujukan teknis. Wass tks.
Pariwisata Berkelanjutan
Terimakasih pak Putra Handara atas masukannya. Artikel ini hanya untuk rujukan konseptual saja bukan rujukan teknis. Memang harus ada pendalaman utk rujukan teknis. Wass tks.
Pariwisata Berkelanjutan
Terimakasih pak Putra Handara atas masukannya. Artikel ini hanya untuk rujukan konseptual saja bukan rujukan teknis. Memang harus ada pendalaman utk rujukan teknis. Wass tks.
Tulisan ini membuka cara…
Tulisan ini membuka cara pandang baru bahwa pariwisata seharusnya tidak hanya mengejar angka kunjungan, tapi bagaimana menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Isu-isu global seperti perubahan iklim, overtourism, sampai dampak pandemi sudah jelas menunjukkan bahwa tanpa arah yang berkelanjutan, pariwisata bisa jadi beban ketimbang manfaat. Untuk Jambi, ini jadi masukan penting supaya kebijakan dan program pariwisata yang disusun bukan hanya kompetitif secara angka, tapi juga benar-benar berkualitas, berakar pada nilai Pancasila, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta generasi mendatang.
Add new comment